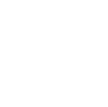Pandangan Muhammadiyah tentang Kepemimpinan Perempuan
Dibaca: 6268
oleh: Muhammad Rofiq Muzakkir (Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)
Topik kepemimpinan perempuan telah cukup lama menjadi diskursus keagamaan yang menarik perhatian Muhammadiyah secara umum dan Majelis Tarjih secara khusus. Sependek pengetahuan penulis, setidaknya ada tiga dokumen dari Majlis Tarjih terkait sikap Muhammadiyah mengenai hal ini. Pertama, buku berjudul Adabul Marah fil Islam yang merupakan produk muktamar khususi Tarjih tahun 1976. Kedua, Fatwa Tarjih tahun 1997 yang termuat dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 4. Ketiga, buku berjudul Wacana Fiqih Perempuan Perspektif Muhammadiyah yang merupakan kumpulan makalah hasil seminar yang diselenggarakan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka tahun 2003. Dokumen pertama lahir sebagai Putusan, dokumen kedua sebagai fatwa dan dokumen ketiga sebagaiwacana atau diskursus keagamaan. Namun demikian, sekalipun karakternya berbeda, isi dari ketiga dokumen tersebut memiliki keserasian pemikiran dan juga ketersambungan gagasan.
Ketiga dokumen tersebut memiliki nilai penting tersendiri bagi warga Muhammadiyah karena memuat pandangan berkemajuan mengenai topik kepemimpinan perempuan. "Pandangan Berkemajuan" perlu digaris bawahi di sini karena inilah karakter yang membedakan Muhammadiyah dari pandangan organisasi lainnya. Pandangan berkemajuan dirumuskan sesuai dengan watak gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid (pembaruan) dan juga sejalan dengan Manhaj Tarjih yang tidak terikat dengan preseden dari masa lalu (pendapat para fukaha). Dalam tiga dokumen tersebut termuat tafsir keagamaan kontekstual terkait nas-nas Al-Qur'an dan hadis Nabi mengenai kepemimpinan perempuan. Tiga dokumen tersebnut juga berisikan pemikiran Muhammadiyah yang melakukan upaya isti'ab wa tajawuz (akomodasi dan lompatan) terhadap dan dari pandangan para ulama klasik. Hal yang masih relevan dipertahankan dan yang dianggap tidak sesuai tidak diakomodir dan, sebagai penggantinya, dikembangkan suatu pemikiran baru yang, pada satu sisi tetap berpijak pada qaedah usuliyyah, amun di sisi lain lebih sejalan dengan kebutuhan masyarakat di era modern
Pandangan Muhammadiyah
Dalam turast (warisan pemikiran) Islam, istilah kepemimpinan diekspresikan dalam berbagai terma, diantaranya imamah, khilafah, imarah, wilayah dan lain sebagainya. Tidak kurang, kepemimpinan perempuan (imamatul marah) juga menjadi bagian dari isu yang didiskusikan oleh para ulama dalam tradisi turast sejak periode klasik. Secara singkat dapat dikatakan di sini bahwa kecenderungan umum yang berlaku di kalangan para ulama adalah menolak kepemimpinan perempuan. Ibnu hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari misalnya melaporkan hal berikut: "ihtajja bi hadis Abi barkah man qala la yajuzu an tuliya al- marata al-qadla wa huwa qaulul jumhur (berhujjahlah dengan hadis Abi Bakrah orang yang berpandangan tidak boleh menugaskan perempuan sebagai hakim dan ini adalah pendapat mayoritas ulama)". Ibnu Hazm bahkan mengklaim bahwa tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin adalah kesepakatan para ulama. Dalam kitabnya Maratibul Ijma' ia menulis: "jami'u firaqi ahlil qiblah laysa minhum ahad man yujizu imamah al-marah (dari keseluruhan kelompok umat Islam tidak seorangpun yang membolehkan kepemimpinan perempuan)".
Muhammadiyah melalui majelis Tarjih mengambil jalan pikiran yang berbeda dari sikap para ulama di atas. Dalam Adabul Marah (1982: 52) disebutkan bahwa "tidak ada alasan dalam agama untuk menolak wanita untuk menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota dan sebagainya". Dalam wacana Fiqh Perempuan pernyataan tersebut dipertegas lagi bahwa untuk jabatan sebagai presiden sekalipun perempuan dapat menempatinya (2005: 50). Dalam Fatwa Tarjih tahun 1997 juga termuat suatu pernyataan, "Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tidak melihat adanya dalil-dalil yang merupakan nash bagi pelarangan perempuan menjadi pemimpin". Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Muhammadiyah mengenai kepemimpinan perempuan, baik di level bawah (kecamatan), komunitas, sampai pada wilayah publik sebagai [residen, yang dalam fikih klasik disebut wilayah uzma (kepemimpinan terbesar), adalah pandangan suportif (memberi dukungan). Pandangan tersebut dilandaskan kepada dalil - dalil yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini:
Pertama, dalil Al-Quran, yang artinya:
Dan orang-orang yang beriman, lelaku dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana [At-Taubah:71].
Ayat di atas adalah suatu bukti tegas bahwa dalam agama Islam kepemimpinan perempuan sangat etrbuka lebar. Setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama dan tanggungjawab yang sama pula sebagai pemimpin. Pintu masuk sebagai penafsiran mengenai bolehnya kepemimpinan perempuan dalam ayat di atas adalah frasa "amar makruf nahi mungkar". Dalam ayat di atas disebutkan bahwa orang-orang mukmin perempuan dan laki-laki saling tolong menolong satu sama lain dalam melakukan amar makruf nahi munkar. menurut majlis tarjih dalam putusannya tahun 1976 termasu dalam kegiatan amar makruf nahi munkae adalah masalah politik dan ketatanegaraan. Dengan perluasan makna amar makruf nahi munkar ayat tersebut kemudian dapat dipahami sebagai dasar bahwa laki-laki dan perempuan mengemban tanggung jawab yang sama dalam urusan kemasyarakatan dan umum sebagai seorang pemimpin publik.
Para ulama menolak kepemimpinan perempuan dengan menyandarkan argumentasinya pada ayat lain, yaitu Q.S 3:34. Ayat ini berbiacara tentang qiwamah laki-laki atas perempuan. Bagaimana Majelis Tarjih memaknai ayat ini? ada dua hal penting yang menjadi sikap Majelis Tarjih dalam emmahami ayat di atas.
Pertama, Majelis Tarjih memaknai ayat ini dengan melaihat asbabun nuzulnya. Sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab tafsir, turunnya ayat ini dilatar belakangi oleh suatu pertengkaran sepasang suami istri. Berdasarkan konteks khusus yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut yaitu tentag masalah rumah tangga, Muhammadiyah kemudian memunculkan sebuah penafsiran yang membatasi pemberlakuan ayat tersebut pada urusan keluarga. Inilah yang disebut penyempitan ruang lingkup ayat (tadyiq nitaq al-ayah) dalam emtode tafsir. Dengan kata lain, menurut Muhammadiyah ayat diatas bukanlah mengenai larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, melainkan ayat tentang peran suami atas istrinya dengan keluarga.
kedua, Muhammadiyah memaknai qiwamah sesuai dengan akar bahasanya. Tafsir-tafsir klasik umumnya memaknai frasa ini sebagai pemimpin, sehingga dari sinilah kemudian berkembang suatu asumsi bahwa laki-lakilah yang berhak memegang jabatan pemimpin publik. Namun, tidak berhak demikian dengan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih yang memaknai kata qiwamah sebagai penanggungjawab. Secara bahasa, qiwamah memang berarti pondasi da ia berasal dari kata qama yang berarti berdiri. melalui akar kata ini dipahami bahwa ayat tersebut sebenarnya menginformasikan bahwa laki-laki adalah penopang, penanggung jawab dan pemikul beban atas perempuan. lakilaki adalah sosok yang membuat keluarga bisa berdiri. Mengenai penafsiran tersebut, ketua majelis Tarjih dan Tajdid, Prof Syamsyul Anwar (2003: 56) mengingatkan bahwa tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu kekuasaan atau dominasi, melainkan imbangan dari tanggungjawab lain yang diembankan oleh sang khalik perempuan, yaitu hamil, melahirkan dan menyusui. ini sejalan dengan makna lain dari qawam yang artinya seimbang. Dengandemikian ayat di atas dapat dipahami bahwa tanggungjawab perempuan. Tanggung jawab tersebut dibebankan dengan cara kewajiban mencari nafkah atau menyangga ekonomi keluarga.
Tulisan pernah diterbitkan di: www.aisyiyah.or.id
Foto: Ilustrasi
Tags: muhammadiyah, aisyiyah, kepemimpinan, perempuan
Arsip Berita