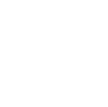Wanita dan Kepemimpinan
Dibaca: 3454
Perlu diketahui bahwa al-Qur’an telah menyebutkan bahwasanya perempuan dan laki-laki setara derajatnya di hadapan Allah (Q.S. al-Hujurat (49): 13), (Q.S. an-Nahl (16): 97), perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi (Q.S. an-Nisa (4): 124), (Q.S. an-Nahl (16): 97). Perempuan dan laki-laki sama-sama diperintah untuk berbuat kebajikan (Q.S. at-Taubah (9): 71). Dari ayat-ayat di atas bisa diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang memuliakan perempuan dan mensejajarkannya dengan laki-laki.
Oleh karena itu, kami pertegas kembali bahwa dalam hal ini Muhammadiyah tetap mengacu pada Himpunan Putusan Tarjih di Wiradesa yang menyatakan kebolehan seorang wanita menjadi pemimpin dengan alasan dan pertimbangan yang telah dipaparkan pada Tanya Jawab agama jilid 4 hal. 240-244 dan dalam buku Adabul Mar’ah fil Islam terbitan Suara Muhammadiyah tersebut di atas.
Dalam hal ini, yang menjadi persoalan adalah mengenai cara memahami hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang menyatakan bahwa:
“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.” [HR. al-Bukhari, an-Nasa’i, at-Tirmidzi dan Ahmad]
Sebagaimana telah diketahui bahwa Muhammadiyah dalam memahami hadis yang diriwayatkan Abu Bakrah ini dengan pemahaman yang kontekstual, tidak terpaku pada teks (pemahaman secara harfiah). Muhammadiyah memahami hadis tersebut dari semangat dan ‘illat-nya (kausa hukum) sebagaimana kaidah usul fikih:
Artinya: “Hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya ‘illat.”
Sedangkan ‘illat dari pernyataan Rasulullah SAW itu adalah kondisi wanita pada waktu itu belum memungkinkan mereka untuk menangani urusan kemasyarakatan, karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman, sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak wanita yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai urusan tersebut.
Lalu mengapa Muhammadiyah harus memahami hadis tersebut demikian? Jawabannya, selain melihat hadis ini dari sisi asbab al-wurud (sebab-sebab munculnya hadis), Muhammadiyah juga melihat hadits ini dari sisi yang lain, sebab hadis ini tidak dapat dipahami berlaku umum. Hadis ini harus dikaitkan dengan konteks saat Rasulullah saw mensabdakannya. Memperhatikan asbab al-wurudnya, hadis ini ditujukan Nabi saw kepada peristiwa pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang meninggal. Bagaimana mungkin hadis tersebut dapat dipahami bahwa semua penguasa tertinggi yang berkelamin perempuan pasti mengalami kegagalan, sementara al-Qur’an menceritakan betapa bijaksananya Ratu Saba’ yang memimpin negeri Yaman sebagaiamana terbaca dalam surat an-Naml (27): 44:
قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. [النمل،]
Artinya: “Dikatakan kepadanya: “Masuklah ke dalam istana.” Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: “Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca.” Berkatalah Balqis: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.”
Oleh karena itu Muhammadiyah mengkontekstualisasikan kerelevanan hadits tersebut dengan realita yang ada pada zaman sekarang. Tentu realita kehidupan pada zaman Nabi Muhammad saw dengan zaman sekarang memiliki perbedaan yang cukup jauh terlebih mengenai permasalahan wanita. Dapat diketahui bahwa wanita zaman sekarang memiliki kemampuan yang hampir sama dengan laki-laki sekalipun secara fisik dan psikis tentu memiliki perbedaan sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ (4): 34;
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. [النسآء
Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”
Memang dalam beberapa kitab dari ulama khalaf maupun salaf hampir sebagian besar dari mereka mengacu kepada pemahaman teks secara harfiah (tekstual) terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah di atas, di antara mereka adalah as-Sayid Sabiq (Fiqh as-Sunnah, jilid 3, hlm. 315) dan as-Shan`ani (Subul as-Salam, hlm. 123). Bahkan di antara mereka ada pula yang menyimpulkan bahwa pemimpin wanita hukumnya haram berdasarkan hadis Abu Bakrah.
Sebenarnya pemahaman tekstual seperti ini tidak selamanya benar, apalagi dalam memahaminya tidak mempertimbangkan dimensi waktu dan ruang yang bisa membuat suatu hukum itu berubah sebagaimana kaidah usul fikih:
Artinya: “Tidak bisa dipungkiri, perubahan hukum bisa terjadi karena perubahan waktu dan tempat.”
Berkaitan dengan pertanyaan Saudara, dengan menggunakan pendekatan di atas, Majelis Tarjih berpendapat tidak ada dalil yang merupakan nash untuk melarang perempuan menjadi pemimpin, baik menjadi hakim, camat, direktur sekolah, lurah, dan lain sebagainya (Adabul Mar’ah fil Islam, hal :76). Laki-laki (mukmin) dan perempuan (mukminat) mempunyai kewajiban yang sama untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar (Q.S. at-Taubah (9): 71) dan melakukan amal salih (Q.S. an-Nisa’ (4): 124).
Bahkan, dalam sejarah Islam Ummu Sulaim dan beberapa wanita Ansar ikut berperang bersama Rasulullah saw untuk mengobati dan membagikan air minum kepada tentara (Adabul Mar’ah fil Islam, hal: 69). Kenyataan sejarah juga menunjukkan bahwa wanita ikut terlibat pada ranah publik, misalnya istri Nabi Muhammad saw, ‘Aisyah yang memimpin langsung perang Jamal, dan Syifa’ binti Abdullah al-Makhzumiyah diangkat menjadi hakim pengadilan Hisbah di Pasar Madinah pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab.
Mengenai hal ini Syaikh Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa setiap perempuan berhak untuk duduk dalam sebuah kepemimpinan di wilayah publik. Hal ini didasarkan pada pemaknaan surat at-Taubah ayat 71, bahwa Allah menetapkan bagi perempuan beriman hak mutlak memerintah sebagaimana laki-laki, termasuk di dalamnya memerintah dalam urusan politik atau untuk kepentingan publik.
Sedangkan hadis yang berbunyi لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةٌmenjelaskan tentang pemimpin atas seluruh penduduk sebuah negeri, atau jabatan kepala negara sebagaimana dapat dipahami dari kata-kata “amrahum” (urusan mereka), maksudnya adalah urusan kepemimpinannya mencakup semua urusan penduduk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan boleh menerima jabatan sebagai pemimpin atau memegang kendali kekuasaan menurut spesialisasi masing-masing, seperti jabatan memberi fatwa dan berijtihad, pendidikan, administrasi dan sejenisnya. (al-Qaradhawi, hal. 529-530)
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Buya Hamka, beliau memaknai surat at-Taubah ayat 71 bahwa orang mukmin laki-laki maupun perempuan, mereka bersatu dan saling memimpin satu sama lain dalam satu kesatuan i’tiqad, yaitu percaya kepada Allah swt. Dengan kata lain, perempuan ambil bagian dalam menegakkan agama, dan membangun masyarakat beriman, baik laki-laki dan perempuan (Hamka, Tafsir al-Azhar hal. 292-293)
Dalam ayat tersebut dapat juga dipahami bahwa kedudukan perempuan adalah mendapat jaminan yang tinggi dan mulia. Terang dan nyata kesamaan tugas perempuan dan laki-laki yang sama-sama memikul kewajiban dan sama-sama mendapat hak. Jadi bukan saja orang laki-laki yang memimpin perempuan, bahkan orang perempuan memimpin laki-laki. (Hamka, hal. 11-12).
Imam al-Baghawiy memberikan alasan bahwa seorang imam (pemimpin) harus keluar untuk berjihad dan mengurus urusan (permasalahan) umat. Sedangkan perempuan tidak mampu untuk mengatur urusan orang banyak (umat) karena ia lemah (li ‘ajziha) dan juga kurang memiliki kecakapan (naqsiha). (Syarh as-Sunnah, juz 10, hal. 77). Hal ini juga diungkapkan dalam kitab Faidl al-Qadir, ( juz 5, hal : 386), Kasyf al-Musykil min Hadis ash-Shahihain (juz 1, hal 325), dan Mirqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih (juz 11, hal: 328). Hal ini menunjukkan bahwa ketika itu perempuan memang kurang memiliki peran dan posisi yang stategis karena beberapa faktor di atas. Sehingga ketidakbolehan wanita menjadi pemimpin harus dipahami sebagai langkah pencegahan (sadd adz-dzari’ah) agar tidak terjadi kekacauan dan ketidakseimbangan dalam pemerintahan. Kaidah usul fikih mengatakan:
مَاحُرِّمَ لِسَدِّ الذَرِيعَةِ أُبِيْحَ لِلْحَاجَةِ
Artinya: “Sesuatu yang dilarang sebagai upaya pencegahan, dibolehkan karena adanya kebutuhan”
Perlu diketahui juga bahwa sifat kepemimpinan pada masa sekarang adalah kolektif kolegial, yaitu melibatkan banyak orang dalam satu pemerintahan. Sehingga seorang perempuan yang menjadi pemimpin, misalnya, tidak harus mengurus semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan karena hal ini akan terasa sangat berat. Ia bisa secara bersama-sama bekerja dengan orang yang terlibat di dalamnya untuk mengurus kepentingan rakyat.
Kesimpulannya adalah, laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk melakukan kebaikan (amal salih) karena keduanya bertanggung jawab untuk memerintahkan kebajikan dan mencegah kemunkaran. Hanya saja, keterlibatan seorang perempuan dalam ranah publik (menjadi pemimpin, misalnya) terlebih dahulu harus memperhatikan dan melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, misalnya mengatur urusan rumah tangga, karena bagaimanapun juga wanita dibebani kewajiban untuk memelihara harta suaminya yang juga mencakup urusan rumah tangga, memperhatikan pendidikan anak (meskipun hal ini merupakan kewajiban suami-istri). Hal-hal di atas perlu diperhatikan agar tidak terjadi kekacauan dalam rumah tangga yang merupakan pondasi utama untuk membangun sebuah peradaban madani.
Perlu juga dipahami amal salih bukan hanya ada dalam ranah publik (baca: menjadi pemimpin). Amal salih harus dipahami sebagai amalan yang sesuai (pantas) untuk dilakukan oleh individu berdasarkan peran dan posisi yang terdapat pada dirinya. Jika peran tersebut telah dilakukan, bolehlah seseorang melakukan pekerjaan lain dengan tetap memperhatikan aturan dan norma agama Islam.
Sumber: Suara Muhammadiyah No 7 tahun 2012
Tags:
Arsip Berita