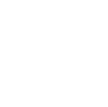Memahami Keindonesiaan
Dibaca: 598
Oleh: Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir
Di negeri ini dan di fora global banyak pihak mencemaskan radikalisme dan politik identitas. Keduanya menjelma menjadi hantu dunia, sebagai problem kehidupan kontemporer seperti ditulis Francis Fukayama dalam karya terbarunya “Identity”. Apalagi jika dibalut kredo fanatik-buta yang menyebar secara tersruktur, sistematis, dan masif dalam kehidupan bangsa-bangsa di era abad 21.
Namun kita layak bertanya. Radikalisme dan politik identitas apa yang sedang ditakutkan itu? Jangan sampai ketakutan berlebihan atas keduanya berubah menjadi bentuk radiaklisme dan identitas radikal baru. Sebaliknya, ketika ada pihak yang tidak mempercayai radikalisme dan menggangapnya sutau ilusi dan konspirasi, berpotensi menjadi proradikalisme.
Sama halnya dengan kecemasan berlebih atas berbagai problem yang mengancam negeri ini. Bahwa Indonesia telah bubar dan hilang kedaulatan oleh asing dan aseng. Meminjam diksi Fukayama, “The End of Indonesia”. Suatu pandangan kritis manakala dikonstruksi ekstrem apalagi disertai politik partisan tanpa topangan pemikiran yang komprehensif, muaranya dapat berpotensi menjadi alam pikiran radikal.
Demikian pula ketika di tubuh bangsa ini terjadi silang sengketa dan saling tuding antar sesama. Komponen Orde Baru menyalahkan Orde Lama, generasi Reformasi menyalahkan dua orde sebelumnya. Setelah itu tumbuh arus balik menterdakwakan Reformasi. Pola pikir sumbu pendek, apriori, dan kacamata kuda bertumbuh menjadi narasi publik saling berseberangan dengan sikap fanatik dan politik partisan.
Masalah bangsa maupun dunia memang kompleks, tidak sederhana seperti dibayangkan khalayak secara dangkal. Masalah ringanpun manakala didekati dengan pikiran dan cara yang keliru bisa menjadi berat dan sulit dicari jalan keluar. Apalagi disertai sikap saling tuding dan menyalahkan, muaranya boleh jadi seperti kata pepatah “menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri”.
Pandangan Radikal
Cemas dan takut akan ancaman itu normal. Sebaliknya menjadi tidak normal kalau hidup tanpa rasa cemas dan takut. Namun ketika semua dihadapi overdosis, boleh jadi yang ditemukan bukan solusi tetapi frustrasi. Sabda Nabi, khyaira al-‘umur auwsathua, sebaik-baik urusan ialah yang tengahan. Ketika dikedepankan pikiran dan sikap ghuluw atau berlebihan, itulah yang disebut ekstrem dan radikal. Pandangan dan sikap ekstrem atau radikal terjadi di semua aspek dan kalangan, karena keduanya merupakan alam pikiran yang mengalir seperti air dan berembus laksana angin ke semua arah kehidupan.
Radikal itu pada dasarnya konsep netral. “Back to radic” atau kembali ke akar, tulis Giddens. Tetapi ketika pola pikir dan sikap “kembali ke akar” atau “kembali ke prinsip” itu bersifat serbadogmatis dan merasa paling benar sendiri kemudian lahir pikiran dan sikap keras, tidak toleran, apologi, dan membenarkan sedikit kekerasan maka itulah yang dimaksud dengan radikal dan radikalisme dalam makna yang berkembang. Sebagian kaum radikal karena antikemapanan, menurut Giddens, bersikap revolusioner meski tidak selalu demikian. Lahirlah sikap serbaekslusif, anti segala hal, dan konfrontasi melawan kemapanan atau apapun yang dipandang berseberangan.
Karenanya perlu seksama memaknai radikal dan radikalisme. Ketika radikalisme dalam berbangsa dan bernegara yang dimaksud adalah setiap paham dan tindakan yang anti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kebhinekaan tentu jelas. Tetapi perlu parameter perundang-undangan yang dapat dijadikan rujukan bersama secara objektif. Sekaligus tidak dikembangkan pandangan orang-perorang maupun golongan yang mengkonstruksi sendiri-sendiri, apalagi menghakimi pihak lain dengan gampang sebagai radikal dan terpapar radikal. Jangan sampai ada pihak yang sekehendaknya bertindak melakukan sweeping terhadap pihak lain yang bersebarangan atas tuduhan radikal. Jika hal itu terjadi berarti sama-sama radikal dan dapat menimbulkan konflik sosial. Isu dan cara menangani radikalisme dengan cara radikal atau deradikalisme berpotensi menimbulkan radikalisme baru dan lebih jauh dapat membelah integrasi nasional.
Semua pihak penting bermushabah dan meninjau ulang pandangan mengenai masalah-masa keindonesiaan, termasuk seputar radikalisme. Pihak yang kritis dan antikemapanan atau bahkan oposisi terhadap pemerintah perlu merefleksi diri apakah pikiran dan tindakannya masih berada dalam koridor kebangsaan yang benar secara konstitusional disertai sikap adil dan ojbektif dengan berpijak pada Pancasila dan kepentingan bersama. Jauhi sikap apriori dan berlebihan yang menyebabkan pandangan dan sikap berbangsa menjadi radikal karena merasa paling benar sendiri sehingga menjurus pada orientasi nonkonstitusional, anarki, disintegrasi, dan hilangnya komitmen kebangsaan yang luhur.
Pihak yang propemerintah juga mesti berpaham dan bersikap moderat dengan berdiri tegak di atas konstitusi dan kepentingan bersama tanpa merasa paling benar dan paling memiliki Indonesia. Jangan merasa paling berkuasa dan memiliki Indonesia sendirian. Siapapun yang mengklaim moderat niscaya menjauhi pandangan dan tindakan radikal atasnama kontra radikalisme, sebab yang terjadi dapat membentuk paham ekstrem tengah atau radikalisme baru. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dengan seluruh institusi negara juga niscaya berdiri tegak di atas konstitusi serta menjalankan kekuasaannya sebagaimana diamanatkan konstitusi dasar dan perundang-undangan dengan kewajiban mewujudkan tujuan nasional secara benar tanpa penyimpangan. Bahwa seluruh lembaga pemerintahan itu milik bangsa dan negara Indonesia, bukan milik satu dua golongan apalagi perorangan!
Perspektivisme
Beragam sikap warga negara atau golongan tentu hadir di Indonesia sebagai bukti bangsa ini hidup dan tidak mati dalam kemajemukan. Mungkin pula ada yang kurang tinggi rasa cintanya pada Indonesia karena berpaham lain dan dipicu berbagai sebab, yang tentu saja tidak perlu terjadi di negeri ini. Ketidakpuasan terhadap keadaan tidak menjadi alasan untuk berpikir dan mengambil langkah inkonstitusional di luar koridor NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada posisi ini mutlak tidak ada ruang bagi bentuk pemerintahan selain Negara Pancasila sebagai “Darul Ahdi wa Syahadah”. Bersamaan dengan itu jangan sampai NKRI pun dibawa pada arah ultransionalisme dan ideologi lain yang bertentangan dengan jatidirnya.
Indonesia tetap harus bebas dari segala bentuk separatisme dan anarkisme. Sebagian pihak terutama di daerah tertentu akhir-akhir ini menunjukkan sikap “separatis” terhadap pemerintah pusat, bahkan karena perbedaan pilihan politik terbersit usulan “referendum”, gerakan seperti ini jangan sampai menjurus radikal dan kontra NKRI. Masalah “konflik ideologi” atau “konflik sosial-politik” seperti itu memang rumit atau kompleks dan sering berkoneksi dengan masalah-maslah lain yang bersifat keagamaan, ekonomi, kedaerahan, budaya, ketertinggalan, dan aspek-aspek lainnya yang bersifat saling-silang kepentingan (cross cuting of interest) atau interkoneksitas dalam kehidupan kebangsaan.
Beragam wajah kebangsaan yang bersifat muktiaspek itu menunjukkan betapa masalah keindonesiaan dan dunia Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara tumbuh dan berkembang tidaklah sederhana dan linier, tetapi kompleks dan gradual sesuai dengan hukum dinamika historis dan sosiologis suatu bangsa. Setiap penyederhanaan atas Indonesia dan keindonesiaan dapat memperdangkal pemahaman akan sejarah kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan Indonesia sebagai negara-bangsa dengan segala kaitannya yang kompleks. Lebih dari itu penting pula dipahami bahwa Indonesia dan keindonesiaan dengan segala dinamika, masalah, dan tantangannya pada saat yang bersamaan di dalamnya terkandung jiwa, pikiran, nilai-nilai dan cita-cita nasional yang menyatu dengan keberadaan Indonesia.
Di sinilah pentingnya memahami Indonesia dan keindonesiaan dalam perspektif yang luas dan mendalam sebagai narasi dan cara pandang memposisikan negara dan bangsa yang besar seperti Indonesia. Suatu ikhtiar memahami negeri kepulauan yang berpenduduk majemuk dengan wajah dan karakternya yang khas, tentu saja perlu dibaca dan dianalisis secara ideografis atau “pemahaman dari dalam secara detail” mengenai perikehidupan Indonesia dan keindonesiaan yang muktiaspek dan multifaktor. Lebih dari itu penting perspektif yang luas dan mendalam dalam mencandra negeri yang kompleks dan sarat dinamika ini agar tidak terjebak pada pandangan dan sikap yang kerdil dan miopik.
Memahami realitas Indonesia dan keindonesiaan perlu pembacaan dan analisis yang multiperspektif karena sangat tidak memadai bila dicandra hanya dengan pandangan yang sederhana dan linier atau instrumental. Sebagian ahli menyebutnya dengan perspektivisme, yakni pemahaman yang melintasbatas dari segala sudut, aspek, da pandangan secara integratif. Kajian-kajian survey yang marak di Indonesia pasca reformasi seputar politik, keragaman atau pluralisme, radikalisme, terorisme, dan persoalan atau isu lainnya yang sering disebut sebagai masalah Indonesia tentu membantu memahami keindonesiaan dan bermanfaat untuk banyak kepentingan membangun Indonesia.
Namun penting pula memberi catatan kritis atas kajian survey tersebut lebih-lebih manakala dikonstruksi secara dangkal, linier, dan parsial karena tidak akan memadai dalam membaca dan menjelaskan Indonsia dengan keindonesiaannya yang kompleks. Bersamaan dengan itu hasil-hasil survey yang terbatas itu jika dipahami secara mutlak dan tunggal maka akan melahirkan bias pemahaman tentang Indonesia dan keindonesiaan di era mutakhir. Survey hanya salah satu cara memahami masalah, bukan satu-satunya, yang memerlukan metode berpikir dan pendekatan keilman lainnya yang bersifat interpretatif, substantif, dan multiparadigma yang nonpositivistik.
Beragam isu masalah keindonesiaan juga menjadi naif manakala dipahami dengan alam berpikir “post-truth”. Opini “Indonesia bubar”, “bencana Indonesia”, “Radikalisme Indonesia” dan segala kegawatan sejenis. Pemikiran kritis apapun tetap terbuka pada kritik (open endeed), jangan dijadikan dokrin dan dogma meski atasnama disiplin ilmu tertentu yang tertutup pada pandangan keilmuan lainnya. Apalagi jika kebenaran sepihak dan dogmatik itu diindoktrinasikan sebagai pandangan tunggal dan absolut menyerupai keyakinan agama dan ideologi, sehingga sebagian orang menerimanya dengan taklid buta. Poltik di era “pasca kebenaran” pun berubah menjadi sarat imaji yang liar, keras, hidup-mati, dan “true believing”.
Di era “post-truth”, kebenaran dikonstruksi atas dasar opini, apriori, prasangka, data bias, dan subjektivitas tertentu yang dipercayai secara mutlak. Dalam argumen Zihao (2018), di era “pasca kebenaran” fakta objektif pengaruhnya sangat lemah dikalahkan oleh argumen emosional dan kepercayaan personal. Lebih-lebih di era media sosial, masyarakat dengan mudah terpapar oleh informasi, opini, dan pikiran yang mentah dan hoak yang dipercayai sebagai kebenaran tak terbantah karena hilangnya daya kritis sekaligus menyebarnya virus pembodohan. Akibatnya, insan modern dan terdidik sekalipun kehilangan jiwa “ulul albab”: “Yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal” (QS Az-Zumar: 18).
*** Tulisan ini dimuat dalam rubrik “Refleksi” Harian Umum Republika, 14 Juli 2019***
Tags:
Arsip Berita