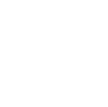Memahami Fikih Muhammadiyah
Dibaca: 359
Oleh: Ilham Ibrahim
Semakin banyaknya pertanyaan “apa hukumnya”, menjadikan fikih kurang elok di mata anak muda sekarang. Kebanyakan dari mereka berpandangan bahwa fikih merupakan kumpulan pendapat ulama dari yang isinya “sedikit-sedikit haram” sampai begitu mudah memberi label halal secara kurang proporsional. Berbicara fikih selalu berujung pada kesimpulan antara halal, haram, makruh, sunah dan mubah. Hal ini terkonfirmasi oleh teman saya yang menyayangkan kenapa perbuatan di dunia harus selalu diukur dengan halal-haram.
Kalau kita membuka traktat fikih klasik, pembicaraan terkait suatu masalah biasanya tidak mudah mendapatkan kesepakatan. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum sesuatu yang diperbincangkan adalah haram, tetapi sebagian lain mengatakan halal. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, misalnya, kita bisa menengok betapa para ulama berdebat hebat dalam memutuskan suatu hukum. Kalau kita cermati, sebenarnya masing-masing dari mereka tidak sembarangan asal bicara. Mereka tentu memiliki argumentasi yang dianggap valid dan kuat. Subyektivitas perumus fikih akan memiliki pengaruh signifikan terhadap corak fikih yang diproduksinya.
Karena itulah, persoalan krusial yang harus segera diketahui publik tentang fikih bahwa ia hanyalah aspek kognitif hukum Islam dan bukan wahyu dari langit (non-divine law). Fikih merupakan produk ijtihad. Oleh karena fikih tak lepas dari konteks spasialnya, maka ia bersifat partikularistik-kasuistik. Ijtihad yang dikeluarkan para ulama memang dipahat untuk merespon tantangan zamannya waktu itu. Dan mujtahid tak lebih dari agen sejarah yang bekerja dalam lingkup situasionalnya, sehingga tak mudah untuk keluar dari konteks yang mereka hadapi. Pandangan mereka bisa jadi cerminan “suasana psikologi umat” di masa lalu, yang sama sekali berbeda secara diametral dengan suasana psikologis dan sosiologis umat Islam masa kini.
Kiranya logis jika pemikiran fikih klasik tersebut diposisikan sebagai pabrik intelektualitas manusia dalam fase dan penggal sejarah tertentu, sehingga tidak bisa diimpor begitu saja ke ruang dan waktu yang berlainan. Sikap inilah yang menjadikan Muhammadiyah berpandangan bahwa ijtihad ulama-ulama klasik merupakan cerminan dari dinamika pergulatan realitas sosio-historis pada era tertentu, sehingga argumentasi mereka hanya sebatas “option” bukan “obligation”. Dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah disebutkan bahwa pandangan imam mazhab itu tidak selalu mutlak, namun argumentasi mereka bisa jadi penambah referensi.
Hal tersebut juga menguatkan bahwa Muhammadiyah tidak memandang fikih klasik sebagai “fahmu turast li al-turast”, pemahaman masa lalu hanya untuk masa lalu. Artinya, dalam menyikapi karya-karya ulama masa lampau, Muhammadiyah memposisikan mereka secara proporsional, dan tidak secara ideologis: tidak membuang seluruhnya tapi juga tidak mengambil seluruhnya. Posisi seperti inilah yang membuat Muhammadiyah begitu fleksibel karena di satu sisi dapat leluasa melakukan pembaharuan, di sisi lain tidak anti dengan warisan ulama klasik. Dengan demikian tidak heran bila karya-karya fikih Muhammadiyah dengan fikih klasik terdapat irisan persamaan dan juga perbedaan.
Perbedaan Fikih Muhammadiyah dan Fikih Klasik
Ciri khas yang paling menonjol dari Fikih klasik adalah ia dibangun atas dalil-dalil yang mendetail (tafsiliyah) dan terfokus pada perbuatan-perbuatan praktis (furu’iyyah). Sehingga wajar bila kitab-kitab yang mereka telurkan begitu panjang memuat perdebatan yang melelahkan seputar aspek-aspek linguistik dan diskusi berbelit-belit terkait halal-haram atau sunah-bidah.
Sementara respons Muhammadiyah terhadap permasalahan sosial-kemanusiaan, tidak selalu dilakukan dengan introduksi norma-norma kongkret yang dilihat dari segi hukum taklifi (halal-haram). Namun juga dengan cara menggali asas-asas agama yang menjadi pedoman dan nilai-nilai dasar kehidupan agar terwujudnya Islam sebagai agama rahmat semesta alam (QS. Al-Anbiya: 107).Dalam Muhammadiyah, norma berjenjang dijadikan sebagai basis dalam membangun paradigma fikih Muhammadiyah.
Fikih Muhammadiyah tidak lagi diidentikkan sebagai sekumpulan hukum praktis yang bersifat furu’iyyah, melainkan totalitas pemahaman terhadap ajaran Islam yang tersusun dari norma berjenjang. Adanya jenjang norma ini menjadikan fikih Muhammadiyah lebih cair dan lentur, tetapi dapat menyapa berbagai masalah kekinian secara arif. Jenjang norma tersebut meliputi nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asasiyyah), prinsip-prinsip umum (al-ushul al-kulliyah), dan ketentuan hukum praktis (al-ahkam al-far’iyyah).
Apabila jenjang norma tersebut dilihat dari atas ke bawah maka jenjang norma pertama ialah nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asasiyyah). Nilai-nilai dasar ini diambil dari nilai universalitas Islam yang diserap langsung dari semangat al-Quran dan as-sunnah. Tingkatan pertama ini bersifat norma-norma abstrak yang merupakan nilai paling esensial dalam ajaran Islam, semisal: nilai tauhid, akhlak karimah, kemaslahatan, keadilan, toleransi, persamaan, persaudaraan, kesetaraan, takwa, kebaikan.
Tingkatan kedua disebut dengan prinsip-prinsip umum(al-ushul al-kulliyyah), yang merupakan deduksi dari nilai dasar dan sekaligus abstraksi dari norma konkret. Prinsip umum ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai dasar menuju hukum terapan yang konkret. Tingkatan kedua ini tercermin dalam kaidah-kaidah hukum Islam yang dirumuskan secara ekspilisit dalam rumusan yuristik singkat dan padat. Semisal ungkapan kaidah fikih yang telah masyhur: “la dlarara wa la dlirara”, tidak rugi dan tidak merugikan.
Tingkatan ketiga berupa norma kongkret atau pedoman praktis (al-ahkam al-far’iyyah) sebagai turunan dari dua jenjang di atasnya. Pada tingkatan ketiga inilah berfungsi mengubah hukum yang tadinya “in abstracto”menjadi hukum “in concreto”. Dengan kata lain, pada jenjang inibarulah kita sampai pada kesimpulan hukum taklifi dan ketentuan hukum wad’i terhadap suatu persoalan.
Ketiga jenjang norma ini tersusun secara hirarkis di mana lapisan norma yang paling abstrak (al-qiyam al-asasiyyah) diturunkan ke jenjang norma yang semi-abstrak (al-ushul al-kulliyyah) dan diturunkan lagi ke jenjang norma yang paling konkret (al-ahkam al-far’iyyah). Misalnya, (1) nilai dasar kemaslahatan, diturunkan menjadi (2) norma yang semi-abstrak seperti kaidah fikih yang berbunyi ‘kesukaran memberi kemudahan’ (al-masyaqqatu tajlib al-taysir), dan asas ini diturunkan lagi menjadi (3) hukum praktis, misalnya: bolehnya berbuka puasa di bulan Ramadhan bagi orang lanjut usia, orang sakit atau ibu yang sedang menyusui seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 184.
Menurut Prof. Syamsul Anwar, dengan menggunakan teori jenjang norma ini, tampak bahwa hukum Islam tidak hanya sekadar kumpulan peraturan hukum konkret detail saja, tetapi juga meliputi asas-asas umum, dan nilai-nilai dasar. Dengan demikian merespons suatu masalah tidak harus selalu dilihat dari logika biner hitam-putih. Tetapi juga dapat dilihat dari perspektif yang lebih umum dari sisi asas-asas dan nilai-nilai dasar hukum Islam. Dari jenjang norma inilah terlahir karya-karya Majelis Tarjih yang berkemajuan seperti Fikih Air, Fikih Kebencanaan, dan lain-lain.
Dengan demikian, tak perlu takut dengan fikih, itu bukan sesuatu yang buruk. Apa yang dibayangkan sebagian orang ketika mendengar kata ‘fikih’ adalah suatu aturan yang sedikit-sedikit membatasi dan menghukumi, meminta darah, dan membatasi rahmat-Nya. Orang yang berpendapat demikian boleh jadi contoh paling aktual manusia yang kurang piknik.
Tags:
Arsip Berita