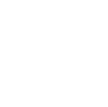Matinya Ruh Sekolah Muhammadiyah
Dibaca: 123
Oleh: Mohamad Ali
Pengasuh Perguruan Muhammadiyah Kottabarat,
Kaprodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
Matinya ruh sekolah Muhammadiyah tidak seketika diikuti dengan terhentinya operasional pendidikan dan mandegnya proses belajar-mengajar. Bisa jadi aktivitas pendidikan di sekolah itu masih berjalan, akan tetapi orientasi ataupun visi yang dibangun bukan lagi membawa nilai-nilai esensial persyarikatan. Secara kasat mata, hal itu dapat dilihat dari eksistensi sekolah yang goyang, rapuh. Bertambah hari, sekolahnya bukan semakin berkembang, tetapi semakin mundur.
K.H. Sahlan Rosyidi, ketua PWM Jawa Tengah dekade 1980-an yang ayahanda Prof. Siti Fadilah Supari, dalam buku Kemuhammadiyah jilid 2 (1983: 57), melukiskan keadaan sekolah Muhammadiyah yang tercerabut ruh kemuhammadiyahannya dengan kalimat berikut: “prestasinya ibarat pasir di atas batu, kemudian jatuh hujan deras atau rintik-rintik, maka sirnalah pasir itu tanpa bekas. Atau, ibarat buih, walaupun secara kuantitas kelihatan tersebar di tengah-tengah lautan, tetapi mudah dimainkan oleh gelombang laut”.
Ilustrasi “pasir di atas batu” ataupun “buih di tengah lautan” untuk melukiskan eksistensi sekolah Muhammadiyah yang telah pudar ruh kemuhammadiyahannya masih relevan untuk membaca peta situasi dewasa ini. Dikatakan relevan, karena masih akurat sebagai pisau analisis dan kerangka referensi untuk membedah persoalan yang dialami pendidikan Muhammadiyah.
Lebih dari itu, ilustasi di atas juga dapat dijadikan ceklist, atau indikator eksistensi sekolah Muhammadiyah. Coba kita renungkan sejenak, berapa banyak sekolah Muhammadiyah yang kedodoran, tiba-tiba rontok muridnya, ketika muncul kebijakan zonasi, sekolah gratis, dan kehadiran sekolah baru di lingkungannya.
Secara jujur harus diakui bahwa, lebih dari separuhnya mengalami kedodoran. Hanya sebagian kecil sekolah Muhammadiyah yang mampu eksis di tengah “hujan lebat” kebijakan pendidikan paska reformasi dan cuaca pendidikan yang tidak menentu. Mereka yang kokoh karena prestasi menjulang dan layanan pendidikan optimal, sehingga tumbuh kepercayaan masyarakat.
Perlu ditelusur lebih seksama, mengapa sekolah Muhammadiyah bisa kehilangan ruh kemuhammadiyahanya. Papan nama sekolah masih memajang nama Muhammadiyah, akan tetapi praktik tata kelola sekolah telah lepas dari nilai-nilai esensial yang dididikkan persyarikatan. Lima nilai esensial Muhammadiyah yang harus menjadi nafas sekolah Muhammadiyah adalah: menumbuhkan cara berfikir tajdid/kreatif-inovatif, mengantisipasi perubahan, bersikap pluralistik, berwatak mandiri, dan langkah moderat (Mohamad Ali, 2010; Haedar Nashir, 2010; Tanfidz Keputusan Muktamar ke-46).
Tiga Jalan kematian
Jalan kematian (kuburan) ruh (nilai-nilai esensial) Muhammadiyah digali sendiri oleh para pengelola (kepala sekolah), penyelenggara (Majelis Dikdasmen), maupun pemilik (persyarikatan), baik dengan sadar maupun tanpa disadari. Prosesnya demikian kompleks dan halus, laksana kodok yang direbus dalam air. Awalnya terasa hangat (terlihat menguntungkan), tidak disadari itu merupakan jalan kematian.
Ilustari jalan kematian kodok direbus dalam air, sangat tepat untuk melukiskan proses memudarnya nilai-nilai esensial persyarikatan dalam pengelolaan sekolah Muhammadiyah hingga menuju ajal. Secara garis besar, penulis mengidentifikasi tiga jalan kematian ruh (nilai-nilai esensial) Muhammadiyah, yaitu ditukarnya alat menjadi tujuan, mentalitas birokratis, dan tanpa perencanan. Ketiganya perlu diurai lebih tajam.
Pertama, sekolah Muhammadiyah yang semestinya sebagai wahana (alat) dakwah persyarikatan ditukar dan dibajak menjadi tujuan itu sendiri. Pesan Kyai Dahlan untuk “menghidup-hidupi Muhammadiyah, bukan malah mencari penghidupan di Muhammadiyah” sangat pas menjelaskan hal ini.
Tidak usah jauh-jauh, lihat sekolah Muhammadiyah di sekitar kita, sekolah sudah sekarat, nafas tersengal-sengal, tetapi ketika mau dibenahi dan lakukan langkah rasionalisasi tidak sedikit yang menentang habis-habisan. Mereka memikirkan penghidupan sendiri terancam, tanpa menghiraukan keadaan sekolah yang tinggal menunggu hembusan nafas terakhir.
Mereka berada di (pengelola-penyelenggara) sekolah Muhammadiyah, bukan untuk menghidup-hidupi dakwah Muhammadiyah melalui jalur pendidikan (memajukan sekolah, tetapi benar-benar hanya untuk mencari penghidupan (mahesah) di Muhammadiyah. Dalam situasi demikian, sekolah Muhammadiyah terjerat oleh pengelola-penyelenggara sendiri yang menukar tujuan besar (dakwah) persyarikatan menjadi sekedar tujuan personal, mencari kehidupan pribadi.
Dalam pengamatan penulis, tidak sedikit sekolah Muhammadiyah yang terjerat (trapped school) dan tengah berada di persimpangan jalan ini. Bila orang-orang yang telah menukar alat menjadi tujuan itu dominan, maka sekolah terjerat ini terus dipelihara, karena menguntungkannya. Akan tetapi, bila orang-orang berpandangan maju dan visioner, yang berani meletakkan kembali sekolah Muhammadiyah sebagai wahana dakawah yang dominan, maka fajar kemajuan sekolah segera terbit kembali beriringan dengan terbitnya matahari di pagi hari.
Jalan kematian kedua, merebaknya mentalitasbirokratis di kalangan pengelola-penyelenggara sekolah Muhammadiyah, sehingga memperlakukan sekolah Muhammadiyah seperti sekolah negeri. Demikian pula pimpinan Majelis Dikdasmen, ia memposisikan diri laksana pegawai Dinas Pendidikan-Departemen Agama. Situasi ini dipercepat seiring pergeseran basis sosial aktivis persyarikatan dari kaum saudagar ke pegawai (PNS).
Secara konseptual, birokrasi dapat dipahami sebagai cara kerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban dan menurut tata aturan (adat-kebiasaan) yang banyak lika-likunya. Mentalitas birokratis berarti mentalitas yang lamban, statis, dan penuh liku-liku. Merebaknya mentalitas ini tentu bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai esensial Muhammadiyah yang mendidikan kemandirian dan kejuangan.
Dengan demikian, merebaknya mentalitas birokratis di kalangan pengelola dan penyelenggara sekolah Muhammadiyah bertentangan dengan nilai-nila esensial Muhammadiyah yang menumbuhkan jiwa kemandirian dan kejuangan. Lebih diri itu, mentalitas birokratis membunuh sekolah Muhammadiyah.
Jalan kematian ketiga, pengembangan sekolah tanpa perencanan dan orientasi pada kuantitas. Ideologi kuantitas begitu dominan menyelimuti penyelenggara maupun pengelola sekolah Muhammadiyah. Dalam definisi mereka, sekolah unggul adalah sekolah yang muridnya banyak. Ideologi ini benar-benar merusak dan menjadi pintu masuk menuju keruntuhan sekolah Muhammadiyah. Tetapi, anehnya, sampai saat ini masih menjadi arus utama.
Suatu SMA Muhammadiyah di kota X pada tahun 1990-an masih diminati masyarakat. Semua pendaftar diterima, seleksi hanya formalitas. Setiap tahun ajaran baru, siswa bertambah, karena kelas belum ada, maka ruang laboratorium/perpustakaan di sulap jadi kelas. Pengelola sekolah disibukkan dengan membangun kelas baru dan mencari guru baru. Memasuki awal 2000 jumlah siswa terus merosot, saat ini hanya ada 20-25 siswa setiap angkatan.
Gambaran di atas banyak dialami sekolah Muhammadiyah, terutama SMP-SMA. Kita tentu tidak mau jatuh pada lubang yang sama, mengelola sekolah tanpa perencanaan dan hanya berorientasi pada kuantitas. Era itu sudah lewat. Hari ini, harus merencankan sekolah secara matang dan benar-benar berorientasi pada kualitas.
Fokus jangka pendek
Dari uraian di atas teridentifikasi tiga masalah mendasar yang diidap sekolah Muhammadiyah yang menjadi jalan lempang matinya ruh (nilai-nilai esensial) Muhammadiyah, yaitu: ditukarnya alat menjadi tujuan, mentalitas birokratis, dan tanpa perencanan-orientasi kuantitas. Masalah-masalah ini perlu ditangani segera, harus serius, dan terarah.
Dalam jangka pendek, langkah yang harus dilakukan adalah mensosialisakan lima nilai esensial Muhammadiyah kepada seluruh penyelenggarara dan pengelola sekolah Muhammadiyah dengan berbagai saluran. Internalisasi cara berfikir tajdid/kreatif-inovatif, mengantisipasi perubahan, bersikap pluralistik, berwatak mandiri, dan langkahnya moderat merupakan kunci untuk menghidupkan kembali ruh Muhammadiyah di dalam dada mereka.
Internalisasi nilai-nilai esensial persyarikatan, baru langkah pertama. Langkah kedua, merintis lembaga riset dan evaluasi yang memfokuskan pada pengembangan sekolah Muhammadiyah. Di setiap wilayah atau daerah yang memiliki Universitas Muhammadiyah harus mengembangkan riset dan evaluasi yang merupakan kolaborasi anatara PTM-Majelis Dikdasmen-Sekolah.
Bukan masanya lagi pengembangan sekolah dilakukan secara serampangan, atau perkiraan-perkiraan belaka. Sebaliknya, harus didasarkan pada riset dan evaluasi yang dijalankan dengan semangat keilmuan. Langkah ke arah ini tidak terlalu sulit, semua tersedia. Yang diperlukan kemauan pimpinan persyarikatan untuk secara serius menggerakan sumber daya manusia maupun finansal yang berserakan menjadi suatu sinergi mutualisme.
Dua langkah ini, bisa dilakukan segera. Tidak harus menunggu setelah muktamar. Tetapi kalau waktunya dirasa sudah terlalu sempit, bisa menjadi rekomendasi untuk menjadi pekerjaan rumah kepemimpinan majelis Pendidikan Dasar dan Menengah berikutnya. Lebih dari itu, bukankah ciri khas gerakan Muhammadiyah dari bawah. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya bila langkah perubahan ini dimulai dari posisi kita masing-masing, saat ini dan di sini.
Tags:
Arsip Berita