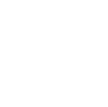Muhammadiyah dan Pancasila: Ki Bagus Hadikusuma dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Dibaca: 389
Oleh: Mu’arif
Muhammadiyah dan Pancasila tidak bisa dipisahkan. Masing-masing dihubungkan oleh berbagai peristiwa penting hingga menjelang detik-detik sidang terakhir PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945. Momen bersejarah bagi Indonesia, sebab berkaitan langsung dengan perumusan UUD 1945, struktur pemerintahan dan konsolidasi nasional pertama. Peran Muhammadiyah selama era ini tidak pelak lagi diperantarai oleh Ketua Umum PB Muhammadiyah, yakni Ki Bagus Hadikusuma dan seorang kader Muhammadiyah bernama Kasman Singodimejo. Selain itu, Bung Karno atau Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, dan Prof. Abdul Kahar Muzakkir, serta Sukiman Wiryosanjoyo merupakan anggota Muhammadiyah. Peran Ki Bagus Hadikusuma selama masa penyesuaian ulang Piagam Jakarta menjadi Pancasila sangat besar.
Ki Bagus Hadikusuma, merupakan tokoh Islam yang sangat penting selama masa konsolidasi konstitusi Indonesia. Ia setidaknya terlibat dalam dua hal selama menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI. Pertama, berkaitan dengan wacana “negara berdasarkan ajaran Islam”, yakni tawaran negara yang mengadopsi nilai-nilai Islam bersama perwakilan muslim lainnya. Kedua, berkaitan dengan perumusan Piagam Jakarta dan Pancasila. Memperjuangkan konsep “negara berdasarkan ajaran Islam” adalah upaya konstitusional pertama untuk mempraktikkan politik Islam. Meski tidak bisa dilakukan karena Ki Bagus Hadikusuma dan pemimpin organisasi Islam serta Masyumi lainnya memaklumi pentingnya nilai keragaman, misi ini tetap berhasil sebagai etika publik Islam yang toleran, moderat dan inklusif. Berkaitan dengan itu, Ki Bagus Hadikusuma juga berperan penting menentukan narasi sila pertama dalam Pancasila.
Perjuangan Politik Islam Ki Bagus Hadikusuma
Perdebatan seputar negara Islam dan Negara Modern (modern-state) telah dimulai sejak digelarnya sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Gagasan yang mengemuka adalah seputar pembentukan negara berdasarkan agama (Islam) atau yang dikenal dengan istilah Darul Islam (istilah sejenis Darus-salam) dan negara sekuler. Sebagaimana diketahui, usulan konsep negara Islam yang diajukan oleh kelompok muslim dan perwakilan organisasi Islam ditolak oleh otoritas pemerintah Jepang yang tergabung dalam keanggotaan BPUPKI. Penolakan tersebut menstimulasi kemunculan dua kubu penting selama masa perdebatan “negara Islam” vis a vis “negara nasionalis-sekuler.” Perbedatan itu juga telah menghadirkan kontestasi ideologi dalam BPUPKI dan PPKI, yakni antara kubu kelompok muslim (baik dari spektrum modernis dan tradisionalis) dan kubu nasionalis (sebagian juga melibatkan politisi muslim, nasionalis, komunis, dan republik).
Soekiman Wiryosanjoyo, Ki Bagus Hadikusuma, Prof. K.H.A. Kahar Muzakkir, K.H.A. Wahid Hasyim, Abikusno Cokrosuyoso, Mr. Ahmad Subarjo, Agus Salim, dan sejumlah nama lainnya merupakan tokoh, politisi dan figur yang mewakili kelompok Muslim dalam sidang-sidang BPUPKI. Salah satu proposal politik yang diajukan adalah konsep “negara Islam” (Dar al-Islam), rumusan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (Piagam Jakarta), dan konsep kepemimpinan Islam. Sidang-sidang BPUPKI antara tanggal 29 April hingga tanggal 7 Agustus setidak-tidaknya telah menyepakati Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945.[1]
Pembubaran BPUPKI yang diiringi dengan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) langsung menggelar sidang-sidang maraton pada tangga 7 hingga 19 Agustus. Keanggotaan PPKI ditambah 6 (enam) orang anggota baru tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang. Dari anggota tambahan tersebut terdapat satu tokoh yang dipandang merepresentasikan kelompok Muslim modernis, yakni Mr. Kasman Singodimedjo (Hadikusuma, Aliran Pembaharuan, h. 102).
Mr. Kasman Singodimedjo adalah tokoh yang menjadi juru kunci pemecah kebuntuan dialog antara kelompok Muslim dengan Nasionalis pada detik-detik akhir sidang-sidang PPKI yang menghendaki penghapusan “7 (tujuh) kata” dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter) (Hadikusuma, Aliran Pembaharuan, h. 103). Kegigihan Kasman meyakinkan Ki Bagus Hadikusuma untuk menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta sebenarnya merupakan suatu bentuk afirmasi terhadap konsep Dasar Negara Indonesia tanpa harus memasukkan ajaran Islam secara formal-eksplisit. Inilah bentuk “kesepakatan bersama” (konsensus)—yang dalam bahasa Kasman disebut sebagai gentlemen’s agreement—dari para pendiri bangsa, terutama dari kelompok Muslim(S.U. Bajasut & Lukman Hakiem, Alam Pikiran, h. 210).
Kesepatakan menghapus tujuh kata dalam piagam Jakarta menunjukkan bahwa visi Negara yang baru lahir itu bukan “negara agama” yang berdasarkan Pancasila, sekaligus juga bukan “negara sekuler” yang memisahkan agama dalam kehidupan politik-kenegaraan. Meski demikian, sebagaimana tampak adanya, ajaran-ajaran Islam tetap diakomodasi dalam sistem konstitusi negara, dan umat Islam dijamin kebebasan untuk menjalankan ajaran agama Islam. Sidang-sidang PPKI setidak-tidaknya telah menghasilkan beberapa keputusan penting: (1) Pengesahan UUD 45; (2) Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden; (3) Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara; (4) Membentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 propinsi.[2]
Polemik Piagam Jakarta dan Pancasila
Perdebatan seputar Negara Islam secara otomatis menghendaki masuknya sumber ajaran Islam ke dalam sistem konstitusi negara. Setelah penolakan konsep Negara Islam, maka strategi perjuangan para tokoh muslim di forum BPUPKI dan PPKI mulai diarahkan untuk memasukkan unsur-unsur ajaran Islam ke dalam sistem konstitusi nasional. Remy Madinier (2013) melukiskan perdabatan keras dan alot tersebut sebagai berikut: “Di balik jalan-jalan pintas yang memudahkan, upaya pemahaman historis hubungan Islam dengan politik merupakan suatu pekerjaan panjang yang melelahkan.”Terutama dinamika politik kenegaraan pada fase pembentukan dasar negara Republik Indonesia dalam sidang-sidang maraton yang diselenggarakan oleh BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Perdebatan tentang konsep negara Islam dan sistem konstitusi negara yang berdasarkan Islam melibatkan tokoh-tokoh Muslim, baik dari kalangan modernis maupun tradisionalis.[3]
Mengenai konsep-konsep awal yang ditawarkan para tokoh nasional dalam rumusan Pancasila tidak akan dibahas di sini. Akan tetapi, rumusan awal yang diajukan Bung Karno pada 1 Juni 1945, dengan susunan dan sistematika yang berbeda, pada akhirnya menjadi kesepakatan bersama (consensus) yang dikenal dengan Piagam Jakarta.Pada mulanya, kelompok Islam baik tradisionalis dan modernis menghendaki masuknya doktrin pokok Islam, yaitu “tauhid” (ajaran mengenai keesaan Tuhan dalam Islam) dan seruan menjalankan “syariat Islam” bagi umat muslim, harus masuk ke dalam sila utama sehingga menjadi “urat punggung” seluruh sila dalam Pancasila. Penambahan redaksional tersebut menyebabkan sila pertama berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”—kemudian dikenal dalam kajian historis dengan istilah “tujuh kata.” Adapun rumusan Pancasila versi awal yang menjadi perdebatan pada waktu itu sebagai berikut:
- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia[4]
Kasman Singodimedjo memiliki peran strategis dalam proses mediasi antara kelompok muslim yang teguh menghendaki masuknya Islam dalam sistem konsitusi negara dengan kelompok nasionalis yang berusaha mengakomodir kepentingan non-muslim. Setelah konsep “Negara Islam Indonesia” ditolak, baik oleh otoritas pemerintah Jepang maupun kelompok nasionalis, maka rumusan “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam sila pertama Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 menjadi kekuatan konseptual yang akan mewarnai sistem konsitusi nasional (Madinier, 2013).
Ki Bagus Hadikusuma, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah, merupakan anggota PPKI yang menghendaki dimasukkannya persuasi kewajiban menjalankan syariat Islam dalam sistem konstitusi negara. Ki Bagus Hadikusuma merupakan figur kharismatik yang disegani oleh kalangan muslim dan kalangan nasionalis (Suara Muhammadiyah, No. 17-18/Th ke-48/September 1968, h. 25-26). Itu juga barangkali yang menyebabkan Soekarno dan Mohammad Hatta segan meyakinkan Ki Bagus Hadikusuma secara langsung untuk menghapus “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta. Panitia Sembilan akhirnya mengirim utusan khusus, Mr. Teuku Muhammad Hasan, yang bertanggung jawab meyakinkan Ki Bagus (Hadikusuma, Aliran Pembaharuan, h. 104-105).
Tetapi proses negosiasi tidak berjalan mulus, Ki Bagus Hadikusuma masih keberatan jika “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta dihapus. Sebetulnya sikap Ki Bagus Hadikusuma mudah dipahami. Bagaimana pun, Piagam Jakarta sebelumnya adalah kesepakatan bersama (gentlemen’s agreement), dan sudah siap diputuskan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Ki Bagus Hadikusuma memegang komitmennya untuk tidak mengubah kesepatan bersama sejak awal. Selain itu, jelas bagi Ki Bagus Hadikusuma, tidak semua Panitia Sembilan terlibat dalam perubahan redaksional Piagam Jakarta. Ketika debat mengalami jalan buntu, dalam jeda waktu yang tersisa, Kasman Singodimedjo berhasil membujuk Ki Bagus Hadikusuma.
Kasman Singodimedjo punya kedekatan ideologis dengan Ki Bagus Hadikusuma karena memang ia tercatat sebagai anggota dan sekaligus kader Muhammadiyah. Kegigihan dan argumentasi logis Kasman berhasil meyakinkan Ki Bagus Hadikusuma agar menerima usul penghapusan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta. Selain faktor kapasitas individu Kasman Singodimedjo, faktor kedekatan ideologis, yaitu hubungan antara keduanya sebagai kader Muhammadiyah, turut menyukseskan proses negosiasi yang cukup alot. Tercapainya kesepakatan bersama dalam rumusan Pancasila seringkali disebut oleh banyak pengamat belakangan ini sebagai “hadiah terbesar” umat Islam untuk bangsa Indonesia. (Hadikusuma, Aliran Pembaharuan…h. 104-105).
“Kompromi politik”—meminjam istilah Kasman Singodimedjo—untuk menyebut tercapainya consensus dalam penyusunan Pancasila sebenarnya merupakan suatu tahapan awal dari proses perjuangan merebut tafsir atas pemahaman dan implementasi setiap sila dalam Pancasila berdasarkan ajaran Islam. Partai Masyumi—yang berafiliasi dengan Muhammadiyah—paling getol mengisi tafsir Pancasila berdasarkan ajaran Islam. Sikap Pengurus Besar (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah sejalan dengan visi Partai Masyumi dalam perumusan dan tafsir atas sila-sila dalam Pancasila. Proses politik di parlemen yang diperankan Partai Masyumi dan didukung oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah terus mengalami pasang surut—sebab partai-partai lain dalam posisi yang berhadapan dengan partai ini, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).
Ki Bagus Hadikusuma dan “Ketuhanan yang Maha Esa”
Menurut informasi dari Djarnawi Hadikusuma, Ki Bagus Hadikusuma bersedia kompromi dengan syarat bahwa redaksi “Ketuhanan” dilengkapi menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan menjadi sila pertama. “Ketuhanan Yang Maha Esa” tiada lain adalah bentuk afirmasi konsep tauhid dalam bentuk yang lebih mudah diterima kelompok nasionalis dan Kristen. Tapi alasan utama mengapa sikap Ki Bagus Hadikusuma melunak, karena ia melihat bangsa yang baru merdeka tersebut membutuhkan kepercayaan diri untuk tampil bangkit sebagai bangsa yang bebas dari kolonialisme. Selain, Ki Bagus Hadikusuma melihat bahwa umat Islam di Indonesia masih dapat memperjuangkan kepentingan keagamaannya melalui jalan konstitusi.
Penerimaan Ki Bagus Hadikusuma pada perubahan redaksional “tujuh kata” berpengaruh pada suasana dan kondisi yang sempat tegang selama beberapa waktu. Penerimaan itu pula telah mempermudah rapat sidang resmi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang terakhir PPKI menerima dengan suara bulat perubahan redaksional Piagam Jakarta. Sebagaimana diketahui, rumusan akhir Pancasila sebagai berikut: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses perubahan redaksional ini telah menjadi peristiwa penting bagi keberhasilan pendiri bangsa mempraktikkan jiwa bangsa yang siap merdeka, menerima perbedaan dan mengedepankan kepentingan hidup bersama sebagai bangsa yang mendambakan kebebasan dari kolonialisme.
Peran Ki Bagus Hadikusuma selama proses perumusan Pancasila merupakan bukti bahwa umat Islam terlibat partisipatif pada masa konsolidasi kebangsaan pertama. Bagi Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusuma merupakan teladan praktik hidup berbangsa. Ia telah memberika petunjuk bagaimana mengamalkan Islam dalam kerangka kehidupan berbangsa dengan komunitas majemuk. Ia pula memberi fondasi pertama bagaimana Muhammadiyah masuk dan mengkhidmati kemerdekaan Indonesia.
*Penulis adalah peneliti sejarah Muhammadiyah
Editor: Azaki KH, Fauzan AS
[1]Iswara N Raditya, “Sejarah Hari Lahir Pancasila: Peran BPUPKI dan PPKI,” https://tirto.id/sejarah-hari-lahir-pancasila-peran-bpupki-dan-ppki-cpMp(Diakses 26 Juli 2019).
[2]Iswara N Raditya, “Sejarah Hari Lahir Pancasila: Peran BPUPKI dan PPKI,” https://tirto.id/sejarah-hari-lahir-pancasila-peran-bpupki-dan-ppki-cpMp(Diakses 26 Juli 2019).
[3]Iswara N Raditya, “Sejarah Hari Lahir Pancasila: Peran BPUPKI dan PPKI,” https://tirto.id/sejarah-hari-lahir-pancasila-peran-bpupki-dan-ppki-cpMp(Diakses 26 Juli 2019).
[4]Iswara N Raditya, “Sejarah Hari Lahir Pancasila: Peran BPUPKI dan PPKI,” https://tirto.id/sejarah-hari-lahir-pancasila-peran-bpupki-dan-ppki-cpMp(Diakses 26 Juli 2019).
Tags:
Arsip Berita